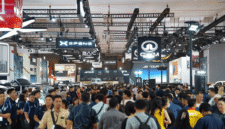Oleh : HARUN
(Koordinator Wilayah Tangerang Raya BEM Banten Bersatu)
Pagi itu di Tual, suasana masih tenang. Seorang pelajar madrasah berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, berboncengan sepeda motor bersama keluarganya usai menunaikan salat subuh. Tidak ada laporan bentrokan besar. Tidak ada situasi darurat yang mencekam.
Namun pagi itu berubah menjadi tragedi.
Berdasarkan keterangan keluarga yang diberitakan sejumlah media, Arianto diduga mengalami tindakan kekerasan oleh seorang anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) saat berada di jalan. Disebutkan terjadi dugaan pemukulan yang menyebabkan korban kehilangan kendali, terjatuh, dan mengalami luka serius di kepala. Arianto sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong.
Pihak kepolisian telah menetapkan anggota yang terlibat sebagai tersangka dan menyatakan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Secara prosedural, langkah itu penting. Namun di ruang publik, pertanyaan yang muncul tidak berhenti pada penetapan tersangka.
Mengapa peristiwa seperti ini kembali terjadi?
Beberapa waktu sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dalam insiden yang melibatkan kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Dalam situasi yang penuh ketegangan, seorang warga sipil kehilangan nyawa. Peristiwa itu memicu evaluasi etik terhadap sejumlah anggota.
Masyarakat pun masih mengingat tragedi di Malang pada 2022, ketika ratusan orang meninggal dunia dalam kepanikan massal di Stadion Kanjuruhan. Meski konteks dan aktornya berbeda, perdebatan yang mengemuka serupa, bagaimana standar penggunaan kekuatan dijalankan di lapangan?
Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar.
Dalam teori penegakan hukum modern, penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Artinya, tindakan harus sah secara hukum, benar-benar diperlukan, dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi.
Prinsip ini bukan sekadar teori akademik. Ia adalah fondasi negara hukum.
Jika ancaman kecil, respons harus kecil. Jika situasi tidak mengancam, maka kekerasan bukanlah pilihan utama. Ketika prinsip ini dirasakan tidak berjalan secara konsisten, kepercayaan publik mulai tergerus.
Kasus di Tual menjadi sangat sensitif karena korban adalah anak di bawah umur. Dalam berbagai instrumen perlindungan anak, negara memiliki kewajiban ekstra untuk menjamin keselamatan dan hak hidup anak. Maka, ketika seorang anak meninggal dalam interaksi dengan aparat, publik secara wajar menuntut transparansi dan evaluasi yang lebih dalam.
Benar bahwa tanggung jawab pidana melekat pada individu. Namun refleksi publik sering kali meluas pada sistem, bagaimana pelatihan dilakukan? Bagaimana pengawasan internal bekerja? Sejauh mana evaluasi dilakukan secara terbuka?
Sejumlah laporan lembaga pemantau hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir juga mencatat adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan sipil. Tidak semua kasus berujung fatal, tetapi cukup untuk menjadi bahan evaluasi berkelanjutan.
Institusi yang kuat bukanlah institusi yang kebal kritik, melainkan yang mampu menjadikan kritik sebagai pijakan pembenahan.
Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya satu peristiwa, melainkan kemungkinan bahwa publik mulai terbiasa dengan berita serupa.
Hari ini pelajar.
Kemarin pekerja ojek online.
Sebelumnya suporter sepak bola.
Jika setiap kasus berhenti pada siklus duka, klarifikasi, dan perlahan dilupakan, maka tanpa sadar kita sedang menormalisasi sesuatu yang seharusnya luar biasa serius, hilangnya nyawa dalam relasi antara negara dan warga sipil.
Padahal dalam negara demokratis, kekuasaan harus selalu dibatasi. Seragam adalah simbol tanggung jawab, bukan dominasi. Kekuatan diberikan untuk melindungi, bukan melukai.
Karena itu, langkah yang diperlukan tidak berhenti pada proses pidana terhadap individu.
Pertama, transparansi penuh dalam setiap tahap penanganan perkara agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penggunaan kekuatan, khususnya dalam interaksi dengan warga sipil dan kelompok rentan seperti anak.
Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel.
Keempat, penguatan pendekatan humanis dalam pelatihan aparat, agar pengendalian diri dan perlindungan hak asasi menjadi budaya, bukan sekadar prosedur.
Kasus di Tual adalah tragedi kemanusiaan. Namun ia juga menjadi momen refleksi tentang bagaimana kekuatan negara digunakan.
Kematian satu warga sipil saja sudah cukup untuk menjadi alarm. Apalagi jika peristiwa serupa muncul dalam ingatan kolektif masyarakat dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh.
Negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat aparatnya, tetapi dari seberapa terkendali kekuatan itu digunakan.
Karena di balik setiap seragam, ada kewenangan.
Dan di balik setiap kewenangan, ada nyawa yang harus dijaga.
HARUN
(Koordinator Wilayah Tangerang Raya BEM Banten Bersatu)